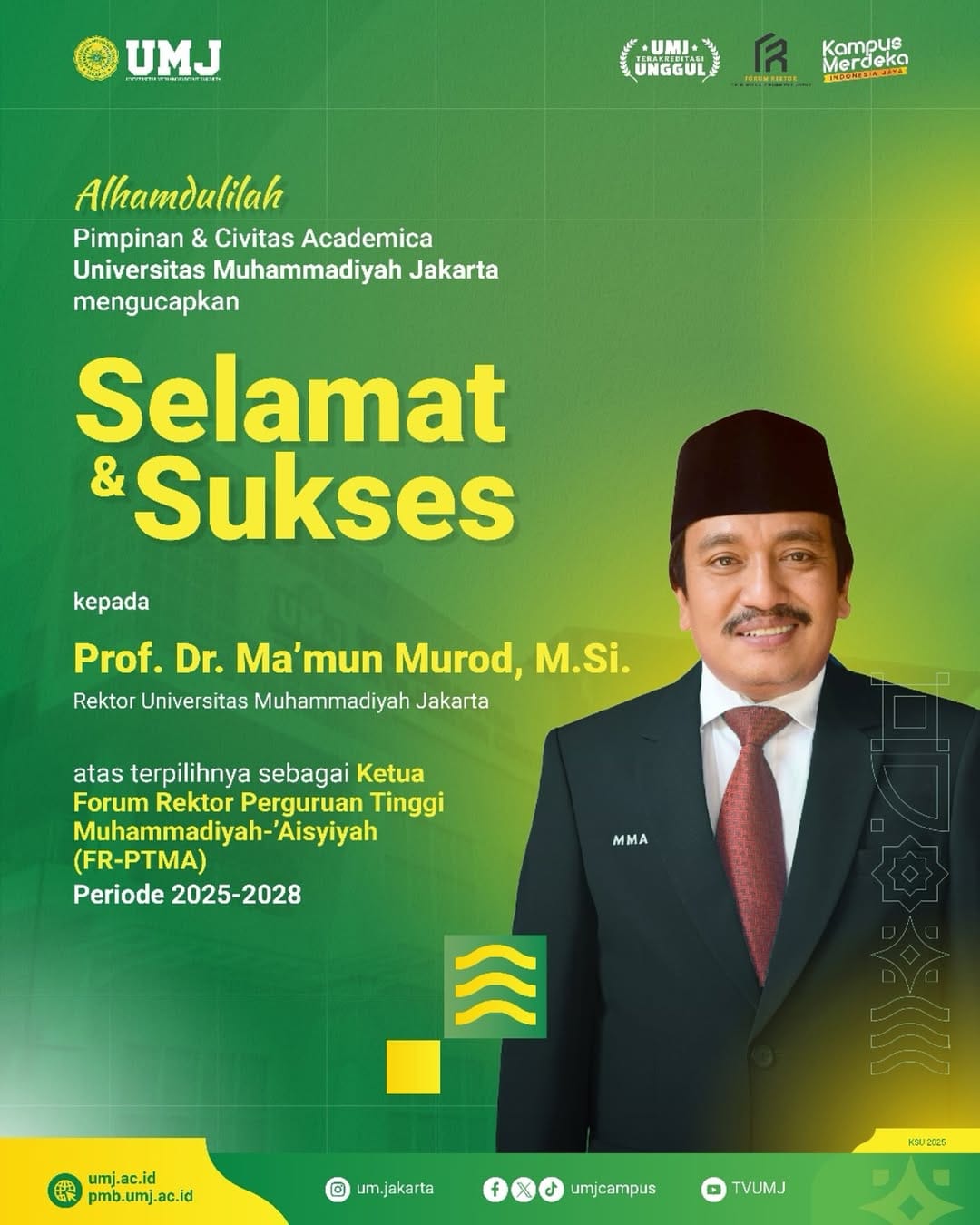ORGANISASI yang hebat tidak dibangun oleh mereka yang lihai menyikut, menyingkirkan, apalagi menggesek kolega demi kursi kekuasaan. Ia dibangun oleh individu yang mengerti cara merangkul, memahami bahwa kebersamaan jauh lebih tahan banting daripada ambisi yang dibungkus intrik.
Namun sayangnya, fenomena “sikut-sikutan” seolah menjadi warna yang mencolok di banyak lembaga, termasuk dalam organisasi keagamaan, pemerintahan, bahkan yang mengaku memperjuangkan nilai-nilai luhur.
Alih-alih menjadi ruang aman untuk tumbuh bersama, organisasi kerap berubah menjadi arena perebutan pengaruh yang saling melukai diam-diam, dari menyabotase agenda rekan, menjegal promosi, hingga menciptakan narasi yang membunuh karakter. Semua itu dilakukan atas nama “perjuangan”. Padahal tak lain hanya kerakusan yang dibungkus dalih idealisme.
Mereka yang paling nyaring bicara tentang persatuan justru kerap menjadi aktor utama dalam fragmentasi. Mereka yang menjual istilah “ukhuwah” atau “solidaritas” di atas podium, diam-diam menyusun strategi penyingkiran terhadap orang-orang yang dinilai mengancam posisinya.
Kita bisa melihatnya dalam dinamika internal banyak organisasi—termasuk yang berbasis keumatan—di mana kader yang unggul bukan dipupuk, melainkan dicurigai. Yang menonjol bukan dirangkul, tapi ditekan agar tidak membayangi. Padahal, organisasi yang sehat justru harus menyiapkan ruang bagi yang lebih muda, lebih cemerlang, dan mungkin lebih kritis. Bukan membenturkan mereka dengan tembok senioritas atau ego jabatan.
Sebuah organisasi yang paham cara merangkul, tidak merasa terancam oleh keberagaman pendapat atau perbedaan latar belakang. Justru di situlah kekuatannya. Ketika semua anggota merasa dihargai, ketika prestasi tak dijegal hanya karena bukan “orang kita”, saat itulah organisasi menjadi rumah, bukan rimba.
Telaah Psikologis: Luka Kolektif dan Ego yang Tak Terjaga
Fenomena ini dapat ditelaah secara psikologis sebagai ekspresi dari inferioritas terselubung. Mereka yang gemar menyikut biasanya menyimpan kecemasan dalam dirinya. Cemas akan kehilangan kendali, cemas akan tertinggal, dan lebih dalam lagi—cemas karena tak mampu bersinar tanpa menjatuhkan cahaya orang lain.
Dalam ilmu psikologi, perilaku tersebut bisa dijelaskan lewat mekanisme pertahanan ego yang disebut projection atau displacement. Individu memproyeksikan kelemahan dan ketakutannya pada orang lain, lalu menjadikan mereka sebagai musuh imajiner. Bukan karena mereka berbahaya, tetapi karena ia sendiri rapuh secara batin.
Luka psikologis yang tidak sembuh, seperti pengalaman disingkirkan, diabaikan, atau tidak dihargai di masa lalu, sering kali membentuk pribadi yang secara tidak sadar mengulang pola itu kepada orang lain. Maka dari itu, tak sedikit para “penyikut profesional” itu adalah mantan korban organisasi, yang bukannya sembuh dan tumbuh, malah memilih menjadi pelaku karena dendam yang belum usai.
Organisasi, jika tidak membangun ruang penyembuhan, hanya akan menjadi pabrik trauma. Dan jika para pelaku luka tidak disadarkan, maka generasi yang datang hanya akan mewarisi penyakit yang sama—dalam versi yang lebih canggih.
Telaah Religius: Antara Amanah dan Hasad
Dalam Islam, organisasi bukan hanya alat perjuangan, tetapi juga ladang ibadah dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Dan menyakiti saudara seorganisasi, menyebar fitnah, menjegal rekan kerja, termasuk bagian dari perusakan ukhuwah yang diharamkan oleh agama.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya.”
(HR. Muslim)
Hasad (iri dan dengki) adalah racun ruhani yang menjadi akar dari budaya saling sikut. Al-Qur’an bahkan menyandingkannya sebagai bagian dari keburukan malam yang pekat:
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ“Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki.”
(QS. Al-Falaq: 5)
Ketika organisasi dijalankan dengan ruh agama yang murni, maka nilai dasar yang harus dijaga bukan hanya program kerja, tapi juga integritas hati para pengurusnya. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang duduk di kursi paling tinggi, tapi siapa yang bisa menahan dirinya dari menyakiti yang lain demi kepentingan pribadi.
Di titik inilah urgensi spiritualitas dalam organisasi menjadi tak tergantikan. Ketika takwa menjadi pilar utama dalam berorganisasi, maka cara bersaing pun menjadi elegan: bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Bukan saling menyingkirkan, tapi saling memberi ruang untuk tumbuh.
Organisasi adalah Cermin Jiwa Kolektif
Organisasi yang hebat bukan tentang seberapa banyak event yang digelar, atau seberapa viral kegiatannya di media sosial. Tapi tentang seberapa besar penghuninya saling menjaga, saling merangkul, dan saling menguatkan. Ia bukan medan perang yang menuntut korban demi kemajuan. Ia adalah taman belajar yang memberi ruang kepada siapa pun yang mau bertumbuh.
Jika organisasi kita hari ini penuh dengan saling sikut, gesek, dan intrik, mungkin saatnya bukan mencari siapa yang salah. Tapi melihat lebih dalam: nilai apa yang telah kita abaikan? Luka apa yang belum kita sembuhkan? Dan apakah kita benar-benar sedang berjuang, atau hanya sedang berlomba memenangkan ego?
Karena sejatinya, organisasi adalah rumah. Dan rumah yang baik, bukan tempat untuk saling sikut. Tapi tempat semua tangan saling merangkul. (*)